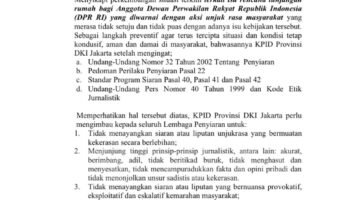KABUPATEN TANGERANG, Suararealitas.co – Di tengah permukiman padat Kampung Bojong Nangka, RT 01/01, Kelurahan Medang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdiri sebuah gapura yang mestinya menjadi pintu gerbang kehormatan warga.
Namun bangunan itu bukan lambang kebanggaan ia kini jadi simbol luka kolektif, memalukan, dan menyakitkan. Ia berdiri lusuh, seolah dipaksa berdiri oleh kontrak, bukan oleh niat baik.
Warga yang melintasi gapura itu setiap hari tidak menyapanya dengan kagum. Mereka meliriknya dengan jijik, sebagian bahkan meludah ke tanah di bawahnya. Karena mereka tahu: yang berdiri di sana bukan bangunan sambutan, melainkan bukti bahwa mereka sedang ditertawakan oleh sistem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang dibangun itu bukan gapura, tapi rasa muak,” kata Uti, warga setempat, suaranya serak karena terlalu sering marah.
“Kalau ini katanya hasil pembangunan, lebih baik nggak usah ada. Lebih baik kami bangun sendiri dari patungan warga, daripada kayak begini, nyusahin hati.”
Tak jauh dari Uti, Suparno berdiri sambil menunjuk ke arah salah satu tiang gapura yang mulai mengelupas. Ia bukan aktivis, bukan akademisi hanya pekerja serabutan dengan logika sederhana. Tapi justru dari mulutnya keluar analisis yang lebih jujur dari seribu pejabat.
“Saya tahu semen yang bagus, saya tahu ukuran besi yang benar. Dan saya tahu ini semua dikerjain asal jadi. Jangan tanya berapa anggarannya, tanya siapa yang berani ngaku bertanggung jawab,” katanya tegas.
“Karena ini bukan salah teknis, ini salah niat.”
Gapura ini menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar dugaan korupsi konstruksi. Ia menjadi wajah dari sistem kekuasaan yang telah kehilangan etika.
Proyek ini, bagi banyak warga, terasa seperti sandiwara anggaran dibangun bukan untuk fungsi, tapi untuk formalitas pengeluaran.
Targetnya bukan kenyamanan warga, melainkan tanda tangan dan tanda terima.
Hilman Santosa, Ketua Poros Tangerang Solid, menyebut proyek ini sebagai bukti banalitas kejahatan dalam birokrasi lokal. Ia menolak menyebut ini sebagai sekadar proyek gagal.
“Ini bukan keteledoran ini niat jahat yang dilegalkan lewat prosedur,” kata Hilman.
“Kalau gapura seperti ini bisa lolos dananya, berarti yang tanda tangan sudah kehilangan rasa malu. Mereka tahu, tapi pura-pura buta. Dan selama rakyat tidak menjerit, mereka akan terus memeras anggaran sambil tersenyum.”
Ia menambahkan dengan nada lebih menusuk: “Ini bukan soal satu gapura. Ini soal satu pola. Mereka uji kita: berani protes atau tidak. Kalau diam, akan muncul gapura busuk lainnya, jalan rusak dengan plang proyek, drainase mampet dengan anggaran ratusan juta. Semua dibungkus laporan pertanggungjawaban yang indah, padahal isinya kebusukan.”
Ironisnya, hingga tulisan ini disusun, tak satu pun pejabat Kecamatan Kelapa Dua memberikan klarifikasi. Tak ada pernyataan, tak ada pengakuan, tak ada evaluasi. Hanya diam seolah mereka yakin, publik akan lupa seperti biasanya.
Tapi kali ini berbeda. Karena yang tercoreng bukan sekadar cat di dinding gapura, melainkan harga diri warga.
Gapura itu kini menjadi semacam tugu pengingat bahwa janji pembangunan bisa menjelma menjadi alat penghisapan. Ia berdiri bukan sebagai penyambut tamu, tapi sebagai penampar wajah warga yang muak dibohongi.
Lebih dari sekadar rusak, gapura itu berbahaya. Bukan karena bisa roboh, tapi karena bisa menormalisasi ketidakberesan. Bisa membunuh harapan warga tentang makna pembangunan. Dan jika itu terjadi, kerusakan sebenarnya bukan di bangunan, tapi di kepala mereka yang membiarkannya.
Maka biarkan gapura itu tetap berdiri. Jangan buru-buru diperbaiki. Biarkan jadi saksi. Karena selama belum ada pertanggungjawaban, belum ada pengakuan dosa, maka gapura itu harus tetap ada sebagai bukti bahwa di titik ini, negara pernah berdiri di atas uang rakyat, dan mencampakkannya dengan licik.
Dan suara-suara seperti Suparno dan Uti hanyalah permulaan. Jika para pembuat keputusan masih terus diam, maka yang akan bangkit bukan hanya protes, tapi perlawanan.