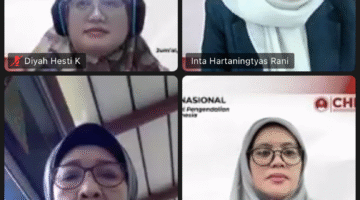Jakarta,Suararealitas.co – Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender (JMS) menyampaikan kritik tajam terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (DBK) yang dinilai belum menjamin pemulihan dan perlindungan yang layak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. JMS menilai substansi peraturan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang seharusnya berpihak pada korban secara komprehensif dan inklusif.
“Sudah tiga tahun UU TPKS disahkan, namun implementasi Dana Bantuan Korban justru mengecewakan. PP ini tidak merefleksikan masukan dari masyarakat sipil, termasuk dari para pendamping korban yang selama ini bekerja langsung di lapangan,” tegas Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JMS menyoroti ketentuan dalam PP yang menyebut bahwa DBK hanya bisa diakses oleh korban yang menempuh jalur hukum (litigasi). Ketentuan ini mengharuskan korban melapor kepada aparat penegak hukum dan menunggu penetapan tersangka, sebelum bisa mendapatkan bantuan. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemudahan akses dan perlindungan tanpa syarat yang berbelit.
Jumisih, Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), menegaskan bahwa mekanisme ini justru menyulitkan korban dari kelompok rentan, khususnya perempuan buruh dan pekerja informal. “Korban dipaksa melalui jalur hukum terlebih dahulu. Padahal, banyak dari mereka sudah trauma, tidak punya akses ke pendampingan hukum, dan takut terhadap aparat,” ujarnya.
Selain itu, JMS juga menyoroti hilangnya peran pendamping korban dalam PP ini. Menurut mereka, pendamping tidak hanya penting dalam proses pelaporan, tetapi juga menjadi saksi dan pelindung pertama korban di lapangan.
Rina Prasarani, Ketua II Bidang Advokasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), menekankan bahwa ketentuan dalam PP DBK tidak mempertimbangkan kebutuhan korban disabilitas. “Pendamping dan korban disabilitas tidak memiliki akses yang memadai dalam regulasi ini. Padahal, keberadaan pendamping sangat krusial bagi korban yang memiliki hambatan komunikasi atau mobilitas,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada sumber dan mekanisme pendanaan DBK. Ketentuan dalam Pasal 14 menyebut dana berasal dari pelaku atau pemerintah, namun tidak menjelaskan secara jelas dari mana anggaran negara tersebut berasal dan bagaimana mekanisme alokasinya. Ini menciptakan ketidakpastian bagi korban yang membutuhkan kepastian dan kecepatan bantuan.
Lusi Peilouw dari Inaata Mutiara Maluku menyatakan, “Kalau pelaku tidak mampu, siapa yang menjamin korban bisa tetap dapat bantuan? Pemerintah harus tegas soal sumber pendanaannya. Jangan hanya andalkan CSR yang bisa saja berasal dari perusahaan bermasalah.”
Terkait pengelolaan dana yang dipusatkan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), JMS menilai hal ini problematis. Mengingat kompleksitas penanganan kekerasan seksual, pengelolaan dana seharusnya melibatkan banyak lembaga lintas sektor.
Sementara itu, Echa Waode, Sekretaris Umum Arus Pelangi, mengatakan bahwa pemusatan DBK di LPSK berisiko mempersempit akses korban, terutama korban dari kelompok minoritas gender dan orientasi seksual. “LPSK masih jauh dari menjangkau kelompok rentan seperti komunitas LGBTQIA+. PP ini harusnya mendorong pendekatan yang berbasis keberagaman identitas korban,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Yeryana, perwakilan Perempuan AMAN dari PHD Barito Timur. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap perempuan adat. “Korban dari komunitas adat sering kali tidak percaya kepada sistem hukum formal. Kalau mereka harus melalui proses hukum dulu baru bisa dapat bantuan, maka mereka akan terus terpinggirkan.”
Selain itu, JMS juga menyoroti lemahnya kapasitas aparat penegak hukum (APH), seperti penyidik dan jaksa, dalam memahami UU TPKS dan PP DBK. Hal ini memperlambat dan bahkan menghambat pemenuhan hak-hak korban. Mereka juga memperingatkan tidak adanya mekanisme pengawasan publik terhadap sumber dana, khususnya dari korporasi yang bisa memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Atas berbagai catatan kritis tersebut, JMS menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Melakukan revisi substansi PP DBK agar sesuai dengan semangat UU TPKS, khususnya dengan mendorong pembentukan trust fund yang dapat diakses korban melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
2. Membangun lembaga koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk menjamin pengelolaan dana secara inklusif, transparan, dan akuntabel, serta menjamin akses mudah bagi korban dan pendamping.
3. Mempercepat pelaksanaan pelatihan terintegrasi bagi aparat penegak hukum untuk memastikan DBK disalurkan dengan prinsip keadilan, tanpa menghambat korban melalui prosedur yang menyulitkan.
“Jika tidak segera diperbaiki, PP ini justru akan menjadi penghalang, bukan solusi bagi pemulihan korban,” pungkas JMS.